Menakar Nasib Sektor Manufaktur
Tulisan Populer 30 Januari 2025 Ananda Febriana Syafitri Read Time 5 minutes
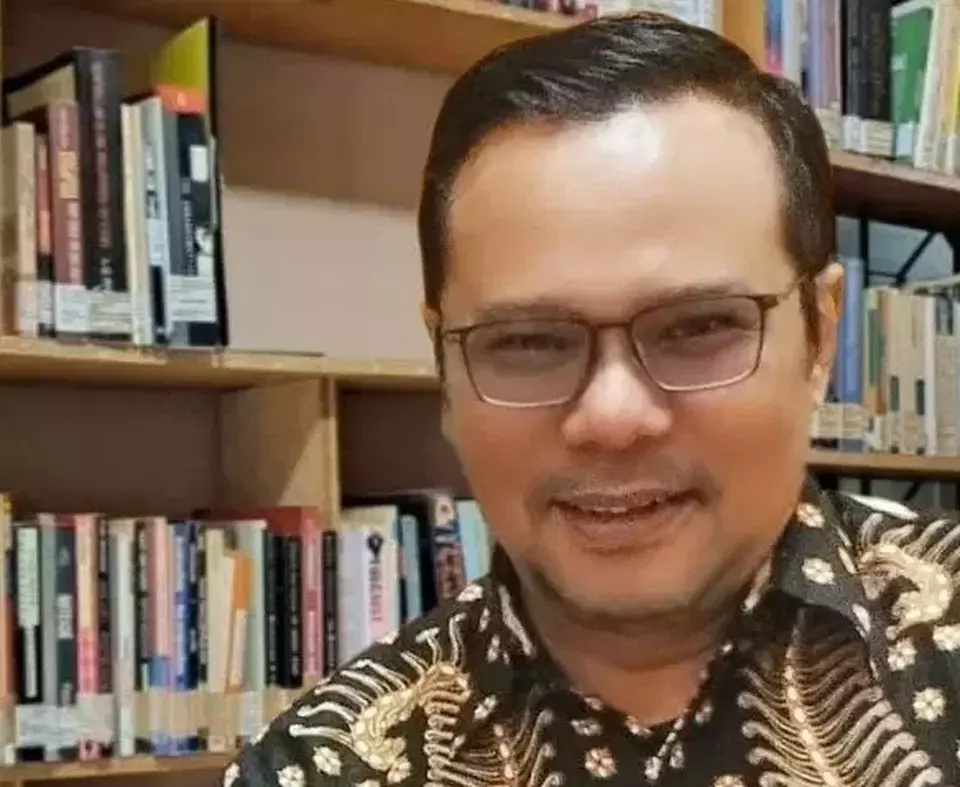
Oleh Hardy R. Hermawan (Mahasiswa Doktoral Perbanas Institute)
Prospek industri manufaktur di Indonesia pada 2025 menjadi perhatian utama semua pemangku kepentingan ekonomi. Target ambisius yang dicanangkan, yakni pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7% pada 2025 dan bahkan mencapai 8% pada 2029, memang memaksa sektor ini menjadi salah satu penggerak utama pencapaian target tersebut.
Dalam peluncuran Peta Jalan Jasa Industri 2025-2045 oleh Kementerian Perindustrian, pada 17 Desember 2024, ditegaskan betapa pentingnya industri manufaktur dalam memastikan pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan, peta jalan jasa industri pun diarahkan untuk mendorong jasa industri menjadi penggerak utama, bukan sekadar pendukung, dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan sektor manufaktur.
Selama ini, sektor manufaktur telah memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor ini menyumbang 18,67% terhadap PDB pada 2023, dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai 0,95% dari pertumbuhan 5,05%.
Pada kuartal III-2024, kontribusi manufaktur meningkat menjadi 0,96% secara tahunan. Untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada 2029, sektor manufaktur harus tumbuh setidaknya 10%. Hal ini menjadi tantangan besar mengingat Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia pada November 2024 hanya mencapai 49,6 poin, menunjukkan kondisi yang masih terkontraksi. Bahkan, nilai kontraktif PMI manufaktur Indonesia, yang berada di bawah 50 poin, sudah berjalan selama lima bulan berturut-turut.
Jelas sudah, sektor manufaktur memerlukan atensi yang serius. Salah satu upaya yang bisa terus dilanjutkan adalah program hilirisasi. Menurut laporan Bank Dunia (2012), hilirisasi dapat meningkatkan nilai tambah produk domestik dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi berbasis sumber daya alam. Hilirisasi industri memainkan peran krusial dalam pengembangan sektor manufaktur di Indonesia.
Penelitian Tabeau et al. (2017) juga menunjukkan, hilirisasi sumber daya alam di negara berkembang dapat meningkatkan nilai tambah secara signifikan, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong industrialisasi yang lebih berkelanjutan. Studi ini menyoroti bahwa negara-negara yang berhasil melakukan hilirisasi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dibandingkan yang hanya bergantung pada ekspor bahan mentah.
Simatupang et al. (2020) juga mengungkapkan, hilirisasi industri di Indonesia, terutama di sektor mineral dan energi, dapat meningkatkan daya saing global dan memperkuat struktur ekonomi domestik. Studi tersebut menekankan perlunya investasi dalam teknologi dan pelatihan tenaga kerja untuk mendukung proses hilirisasi yang optimal.
Hilirisasi memang bisa menjadi kunci untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja berkualitas. Tanpa itu, target pertumbuhan tinggi sulit dicapai. Saat ini, pemerintah Indonesia sudah memilih hilirisasi grafit dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik sebagai prioritas utama untuk mendorong pertumbuhan manufaktur.
Namun, berbagai tantangan juga terus membayangi sektor manufaktur. Salah satu isu utama adalah iklim usaha yang kurang kondusif. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) kerap menyatakan, biaya siluman dan praktik pungutan liar terus membebani pelaku usaha. Masalah perpajakan, seperti perbedaan tarif pajak daerah, juga menjadi hambatan investasi. Ketidakpastian aturan pajak di Indonesia banyak menyebabkan pelaku usaha mengalami kerugian.
Kenaikan PPN menjadi 12% juga dapat berdampak signifikan pada industri manufaktur. Menurut studi Siregar et al. (2023), peningkatan PPN cenderung menaikkan biaya produksi hingga 3-5%, yang pada akhirnya diteruskan kepada konsumen melalui kenaikan harga barang.
Dalam jangka pendek, kenaikan PPN membuat daya beli masyarakat menurun sehingga memengaruhi penjualan manufaktur domestik. Dalam jangka menengah, perusahaan menghadapi tekanan untuk meningkatkan efisiensi agar tetap kompetitif. Ahmad dan Setiawan (2022) juga mencatat bahwa ketidakpastian kebijakan perpajakan dapat menghambat investasi, memperlambat ekspansi kapasitas produksi manufaktur hingga 15% selama dua tahun pertama.
Tantangan lainnya adalah maraknya barang impor ilegal yang menggerus daya saing produk lokal. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa nilai barang impor ilegal pada 2024 mencapai Rp62 triliun, meningkat 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
Dari sisi konektivitas, keterbatasan infrastruktur logistik juga menjadi kendala signifikan. Studi Bank Dunia pada 2023 menempatkan Indonesia di peringkat ke-46 dalam Indeks Kinerja Logistik, jauh tertinggal dibandingkan negara-negara Asean lainnya seperti Singapura dan Malaysia. Jurnal Transportation and Logistics in Southeast Asia (2022) menyoroti bahwa efisiensi logistik Indonesia hanya mencapai 67% dibandingkan Singapura yang berada di angka 94%. Keterbatasan ini memperlambat akses ke pasar ekspor yang seharusnya menjadi andalan untuk mendorong pertumbuhan manufaktur.
Di saat yang sama, hubungan industrial yang stabil juga menjadi prasyarat penting. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa pada 2024 terdapat 3.800 kasus perselisihan hubungan industrial, dengan mayoritas terkait masalah upah dan PHK. Padahal, peningkatan produktivitas hanya dapat tercapai jika hubungan antara pekerja dan pengusaha harmonis.
Konflik hanya akan memperburuk situasi. Sebuah studi dalam Jurnal Hubungan Industrial Asia Pasifik (2023) juga menunjukkan bahwa 40% konflik hubungan kerja di Indonesia disebabkan oleh ketidakjelasan kontrak kerja dan sistem pengupahan yang tidak transparan.
Masalah lain yang tidak kalah penting adalah keterampilan dan kompetensi tenaga kerja. Data BPS menunjukkan bahwa pada 2023, sekitar 55% angkatan kerja hanya memiliki pendidikan setara SMA atau lebih rendah. Laporan Human Capital Development in Indonesia (2023) menyoroti bahwa kurangnya pelatihan vokasional dan sertifikasi menjadi kendala utama bagi daya saing tenaga kerja di sektor manufaktur.
Dari belahan dunia lainnya, tantangan global juga tidak bisa diabaikan. Ketegangan geopolitik dan perlambatan ekonomi dunia pada 2024 berdampak pada turunnya permintaan ekspor. Volume ekspor manufaktur Indonesia pada 2024 hanya tumbuh 2,5%, jauh di bawah target 5%.
Untuk itu, diversifikasi pasar ekspor menjadi agenda mendesak. Indonesia harus terus memperluas pasar ke Afrika dan Timur Tengah. Ketergantungan pada pasar tradisional seperti Amerika dan Eropa terlalu berisiko.
Dihadapkan pada persoalan-persoalan itulah, Kementerian Perindustrian dituntut untuk mampu menggerakkan sektor manufaktur secara efektif dan terorkestrasi. Meski menghadapi pemotongan anggaran sebesar 34% menjadi Rp2,51 triliun pada 2025, Kementerian Perindustrian tetap harus menjamin agar keberhasilan pembangunan industri tidak semata-mata bergantung pada APBN. Peran sektor swasta dan kebijakan yang tepat menjadi jauh lebih menentukan saat ini.
Harapan ini juga didukung oleh potensi sektor manufaktur untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Data BPS menunjukkan bahwa industri manufaktur mempekerjakan lebih dari 18 juta orang pada 2023, atau sekitar 14% dari total angkatan kerja.
Dengan pertumbuhan yang lebih tinggi, sektor ini diharapkan dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, yang sangat diperlukan untuk mengurangi angka pengangguran nasional yang masih berada di kisaran 5,8% pada 2024.
Meski teramat berat, target mencapai pertumbuhan manufaktur double digit untuk menunjang partumbuhan ekonomi 8% tetap harus diupayakan. Nah, mampukah Indonesia mencapai target itu? Kita lihat saja. Yang jelas, tahun 2025 ini yang akan menjadi tahun penentuannya.